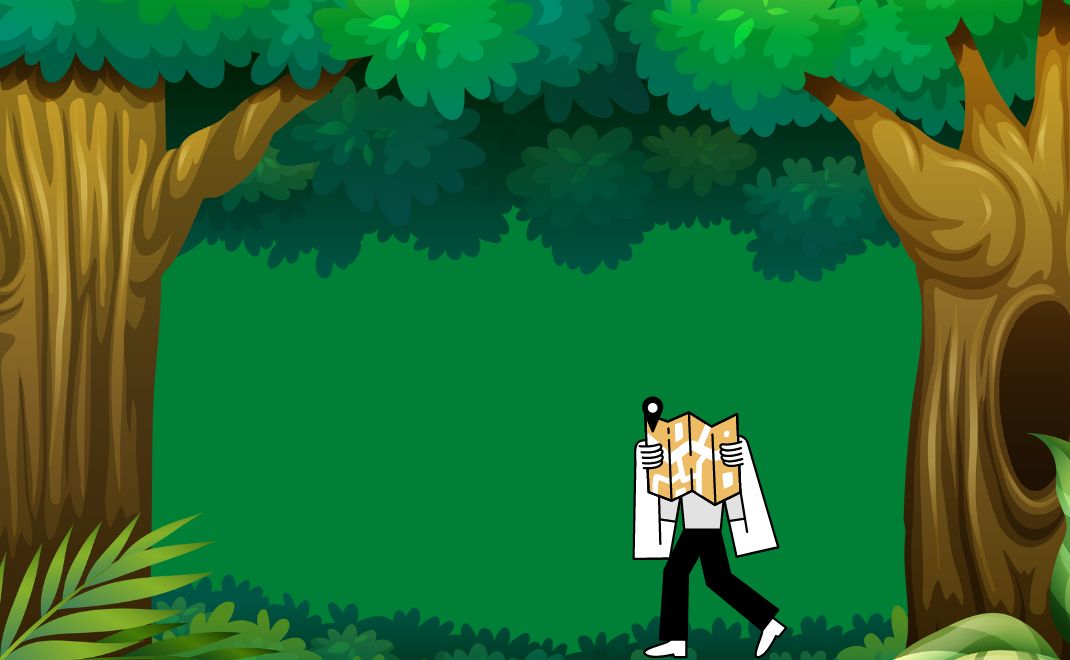
AGAKNYA kita kurang memperhatikan atau bahkan mungkin kurang belajar dari apa yang terjadi dalam pengelolaan hutan. Jumlah perusahaan pengelola hutan produksi (HPH) berkurang separuh sejak 1970-an, tinggal 251 unit. Perusahaan hutan tanaman (HTI) yang produktif umumnya yang tergabung usaha besar. Artinya, dalam lebih empat dekade 35 juta hektare hutan produksi telah kehilangan produktivitasnya.
Dengan kenyataan itu, penting kita menguji kembali apa yang harus kita yakini dalam pengetahuan kelestarian hutan dan apa yang harus kita kritisi, bahkan harus kita tinggalkan. Pengelolaan hutan telah membuktikan kesalahan. Tapi tak ada reaksi dari para pelaku kehutanan untuk menunjukkan ada “wicked problem” atau “masalah jahat”, yang ditangani dengan cara pikir teknikal, hukum, dan administratif. Kata “jahat” di sini bukan penilaian moral.
Dalam buku yang dipublikasikan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) “Debate the Issues: Complexity and policy making” pada 2017, Julia Stockdale-Otárola menjelaskan bahwa masalah jahat bersifat dinamis, tidak terstruktur dengan baik, terjadi terus-menerus dan bersifat sosial yang melibatkan banyak aktor dan selalu terkait dengan masalah sosial lainnya.
Masalah seperti itu dipengaruhi oleh berbagai domain kebijakan dan tingkat pemerintahan, sehingga intervensi apa pun akan memicu rantai konsekuensi baru yang tidak diinginkan.
Semua faktor itu, tulis Stockdale-Otárola, menyulitkan siapa saja menyepakati apa masalah sebenarnya, di mana akarnya, siapa yang bertanggung jawab, dan cara terbaik mengatasinya. Cakupan masalah jahat juga tidak jelas. Seluruh sistem bisa terlibat. Ironisnya, problem kehutanan Indonesia hanya dianggap sebagai masalah sektoral, manajemen hutan, silvikultur, pembukaan wilayah, hukum, maupun administrasi. Bahkan hal-hal itu sering dipikirkan secara terpisah.
Dengan memperhatikan pengelola hutan alam produksi yang terus berguguran, masalah jahat yang diselesaikan dengan cara sektoral itu tampak menjadi lebih buruk. Penyelesaian masalah kebijakan dengan cara tradisional, apabila ditelaah dengan metafora ekonomi, hanya dilakukan dengan biaya termurah, berpikir sempit, dan teknikal. Biaya mahal akan dihindari, yaitu memikirkan kompleksitas penentu keberlanjutan di luar sektor ini.
Biaya murah itu tecermin dari, misalnya, regulasi sebagai standar kerja dengan hukuman dengan skema “atur dan awasi”, bukan mencegah perilaku menyimpang. Padahal selama hutan alam produksi yang potensinya tidak dibukukan, tidak akan membuat kerugian bagi siapa pun bila rusak. Kondisi ini mendorong pengelola hutan membiarkan kerusakan, walaupun sejumlah pedoman kerja untuk menghindarinya diterapkan dan bila dilanggar ada hukumannya (Kartodihardjo, 1998).
Kebijakan dengan cara tradisional itu bukan hanya menyangkut pengaturan pemanfaatan hutan alam produksi saja, juga diterapkan di seluruh pengelolaan hutan, termasuk konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan. Hal itu terungkap dalam pembahasan mengenai peran dan kinerja kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebelum dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja, pada awal bulan ini.
Pembahasan itu mengungkap bekerjanya paradigma pengelolaan hutan “atur dan awasi” dengan kerangka kerja yang serupa dengan “totalitarianisme”. Sejak akhir 1970-an, yang menentukan hampir semua kegiatan dituntun oleh peraturan dan pedoman. Sangat jelas bahwa paradigma itu ingkar terhadap fakta kompleksitas dan masalah jahat yang telah melingkari kehidupan kehutanan.
Sehingga, “gajah kehutanan” hanya dilihat sebagai bagian-bagian tubuhnya. Dalam perkembangannya, cara seperti itu membawa akumulasi masalah di masa depan sehingga meningkatkan tingkat kompleksitas dan masalah jahat yang disebut Stockdale-Otárola itu.
Saat inilah masa depan itu. Tapi kita masih meyakini berbagai problem masih ditangani dengan biaya murah lewat penyederhanaan masalah.
Laporan OECD yang lain, “Applications of Complexity Science for Public Policy: New Tools for Finding Unanticipated Consequences and Unrealized Opportunities”, menyebut bahwa pejabat pemerintah dan pembuat keputusan semakin menghadapi sistem sosial yang rentan terhadap perilaku yang mengejutkan, perubahan kecil yang berdampak besar. Sebaliknya, perubahan besar memiliki efek yang sangat kecil untuk berbagai efek yang datang dari penyebab yang tidak terduga.
Hal itu berarti sistem sosial, politik, ekologi, dan ekonomi kehutanan terlibat dalam interaksi yang saling adaptif, tidak tetap, bukan hubungan linier. Di situ perlu pembaruan cara berpikir kelestarian hutan, yang kini masih terperangkap dalam tataran teknis pengaturan hasil hutan yang ditebang atau dipungut. Artikel saya “Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial” telah menjelaskan pentingnya penyesuaian cara berpikir ini.
Dari pengalaman saya selama ini, pembaruan, apalagi menyangkut fondasi cara berpikir, akan selalu menemukan hambatan. Hampir selalu ada masalah untuk menjalankan solusi. Dalam hal ini saya telah menyusun artikel “Belenggu Tupoksi” yang memberi alasan mengapa hal itu terjadi.
Meskipun tidak ada formula ajaib, pendekatan menangani kompleksitas kehutanan dan masalah jahatnya, bila dilaksanakan, akan membantu menangkap seluk-beluk masalah jahat itu.
Sebagai contoh, pemerintah Singapura memperkenalkan campuran pendekatan kebijakan mengatasi masalah jahat di negaranya. Misalnya, pendekatan matriks untuk membantu segenap departemen atau unit kerja berbagi informasi dengan lebih baik dan bekerja bersama secara horizontal. Ada unit kerja baru untuk mengatasi masalah yang paling sulit, berserta komputerisasi untuk membantu mengurangi risiko sistemik.
Alih-alih mencoba menemukan solusi akhir menghadapi kompleksitas dan masalah jahat pengelolaan hutan, secara umum, yang paling baik adalah mengelolanya meski tidak sekaligus menyelesaikannya. Intinya, kita perlu lebih fleksibel mengelola tantangan masalah jahat dengan lebih baik. Kebijakan harus adaptif, sehingga sejalan dengan fakta lapangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kita juga perlu menghindari menjadi terlalu terikat pada solusi kita sendiri, karena penghambat atau pendorong datang tak terduga.
Tidak seperti masalah konvensional, di mana protokol berbasis ilmiah bisa memandu pilihan solusi, menemukan navigasi masalah jahat pengelolaan hutan hanya perlu berhenti berpikir menjalankan pedoman standar yang kaku. Lalu terus belajar menemukan solusi yang adaptif.
Ikuti perkembangan terbaru tentang pengelolaan hutan di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :
















