
KITA acap beranggapan ketidaktahuan terkait dengan soal minimnya data atau informasi. Menurut Hariadi Kartodihardjo, ketidaktahuan lebih sering lahir dari hilangnya konteks dan sempitnya cara pandang terhadap persoalan yang kompleks.
Praktik kehutanan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tampak logis di atas kertas, tapi kehilangan makna ketika bersentuhan dengan realitas di lapangan. Apa penyebabnya?
Para pembuat kebijakan terlalu percaya pada angka-angka statistik dan laporan administratif, tanpa benar-benar memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Akibatnya, solusi bersifat generik dan tidak kontekstual, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ketika kebijakan diterapkan, muncul berbagai persoalan baru mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat, kegagalan program rehabilitasi, hingga konflik tenurial yang berkepanjangan. Hal ini memperlihatkan data dan informasi yang melimpah tidak serta-merta menjamin kebijakan yang efektif, jika tidak diiringi dengan pemahaman terhadap konteks lokal.
Maka penting bagi para pengambil keputusan untuk tidak sekadar mengandalkan pendekatan teknokratik, namun membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mengakui keberagaman pengetahuan lokal. Dengan memahami konteks secara utuh, kebijakan kehutanan di NTB dapat dirancang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Ketidaktahuan bukan lagi soal kurang data, melainkan kegagalan membaca realitas. Inilah tantangan terbesar dalam tata kelola kehutanan kita hari ini.
Pada tataran implementasi, program-program seperti rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) di NTB acap hanya menjadi rutinitas administratif. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, cenderung mengedepankan pendekatan teknokratik yang menggeneralisasi masalah degradasi hutan dan minimnya partisipasi masyarakat.
Ketika kebijakan ini dijalankan, Kelompok Tani Hutan (KTH) lokal hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis, tanpa ruang untuk mengekspresikan pengetahuan lokal, kebutuhan riil, atau bahkan dinamika internal kelompok mereka. Akibatnya, solusi yang ditawarkan justru melahirkan masalah baru, seperti kegagalan tanaman tumbuh akibat minimnya pemeliharaan dan insentif jangka panjang.
Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelibatan KTH hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi. Mereka diminta menanam bibit sesuai target, mengisi laporan, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dari atas, tanpa pernah benar-benar diajak berdiskusi mengenai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat atau strategi pemeliharaan yang efektif.
Setelah proyek selesai dan laporan diserahkan, perhatian terhadap keberlanjutan tanaman pun terabaikan. Ketiadaan insentif jangka panjang dan minimnya pendampingan membuat banyak tanaman yang akhirnya mati, sehingga tujuan utama program yakni pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai.
Kondisi ini memperlihatkan keberhasilan program kehutanan tidak bisa hanya diukur dari capaian administratif atau jumlah bibit yang ditanam. Diperlukan perubahan pendekatan yang lebih partisipatif, di mana pengetahuan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat lokal benar-benar menjadi dasar dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Hanya dengan cara ini, program-program kehutanan dapat memberikan dampak yang nyata, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab tantangan di lapangan.
Fenomena pseudo-solusi ini, sebagaimana dikemukakan Cleaver (2002) dalam konsep "institutional bricolage", memperlihatkan betapa kebijakan yang tidak berpijak pada praktik kelembagaan lokal hanya akan menjadi beban administratif.
Regulasi yang dibawa dari luar, tanpa mempertimbangkan sistem pengelolaan air tradisional, tata cara pembagian hasil, atau struktur kewenangan adat, gagal menjadi instrumen pemecahan masalah. Sebaliknya, ia justru memperkuat jarak antara negara dan masyarakat, serta memperbesar potensi konflik dan ketidakpercayaan.
Dalam praktiknya, beban administratif ini memaksa kelompok masyarakat untuk mengikuti prosedur yang rumit dan tidak relevan dengan kebutuhan sehari-hari mereka.
Banyak KTH yang akhirnya lebih sibuk mengurus dokumen dan laporan ketimbang mengelola hutan secara efektif. Ketika aturan formal yang diimpor dari luar tidak selaras dengan norma dan praktik lokal, masyarakat cenderung merasa terasing dari kebijakan yang seharusnya mereka jalankan.
Akibatnya, kebijakan tersebut tidak hanya gagal mencapai tujuannya, juga menimbulkan resistensi, memperlemah kepercayaan pada pemerintah, dan bahkan memicu konflik horizontal maupun vertikal di tingkat tapak. Hal ini menegaskan pentingnya desain kebijakan yang benar-benar menghargai, mengakomodasi, dan memberdayakan kelembagaan lokal agar solusi yang dihasilkan tidak sekadar administratif, melainkan juga substantif dan berkelanjutan.
Lebih jauh, kegagalan memahami hutan sebagai ruang hidup masyarakat bukan sekadar entitas ekologis yang steril dari aktivitas manusia menjadi akar dari ketidaktahuan kebijakan kehutanan di NTB. Banyak kawasan hutan yang secara legal memang berstatus sebagai milik negara, namun dalam praktiknya telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sekitar selama puluhan tahun.
Hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang sosial, budaya, dan spiritual yang membentuk identitas serta pengetahuan lokal masyarakat. Di sana, masyarakat telah mengembangkan sistem pengelolaan tradisional, aturan adat, dan mekanisme berbagi hasil yang terbukti mampu menjaga keberlanjutan hutan.
Namun, ketika negara hadir dengan pendekatan “command and control” di mana kebijakan dirancang secara sentralistik dan implementasi dilakukan tanpa dialog relasi sosial yang sudah terbangun ini seringkali diabaikan.
Negara cenderung memaksakan aturan formal yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan lokal, seperti pembatasan akses, larangan pemanfaatan, atau penetapan kawasan konservasi tanpa konsultasi. Akibatnya, intervensi yang dilakukan justru kontraproduktif: masyarakat kehilangan rasa memiliki terhadap hutan, muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan tidak jarang terjadi konflik tenurial yang berkepanjangan.
Situasi ini mempertegas pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan. Kebijakan yang efektif harus mampu mengakui dan mengintegrasikan relasi sosial-ekologis yang sudah ada, serta memberikan ruang partisipasi yang nyata bagi masyarakat.
Hanya dengan mengedepankan dialog, menghargai pengetahuan lokal, dan membangun kolaborasi, pengelolaan hutan di NTB dapat benar-benar berkelanjutan dan adil, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat yang menggantungkan hidup padanya.
Dari sini, menjadi jelas bahwa ketidaktahuan dalam kebijakan kehutanan bukan sekadar soal kurangnya data, melainkan kegagalan memahami konteks sosial-ekologis yang kompleks. Solusi yang tidak berbasis pada pembacaan menyeluruh terhadap konteks akan terus jatuh pada jebakan pseudo-solusi terlihat sibuk menyelesaikan masalah, namun sebenarnya hanya menambah daftar masalah baru.
Sudah saatnya kita mengubah paradigma dalam perumusan kebijakan kehutanan. Solusi yang efektif adalah solusi yang “berakar” mengakar pada realitas lokal, menghargai perspektif masyarakat, dan membuka ruang bagi fleksibilitas kelembagaan. Pendekatan ini tidak hanya lebih adil secara sosial, tetapi juga lebih berkelanjutan secara ekologis.
Sebagaimana refleksi dalam buku Hariadi Kartodihardjo, kita perlu berani mengakui bahwa ketidaktahuan kerap kali adalah akibat dari kehilangan konteks dan sempitnya cara pandang. Jika kita ingin solusi benar-benar menjadi solusi, maka mendengarkan, memahami, dan melibatkan masyarakat lokal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Hanya dengan begitu, praktik kehutanan di NTB dan di Indonesia pada umumnya, dapat keluar dari lingkaran pseudo-solusi dan menuju tata kelola yang lebih bermakna dan berkelanjutan.
Ikuti percakapan tentang kebijakan kehutanan di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
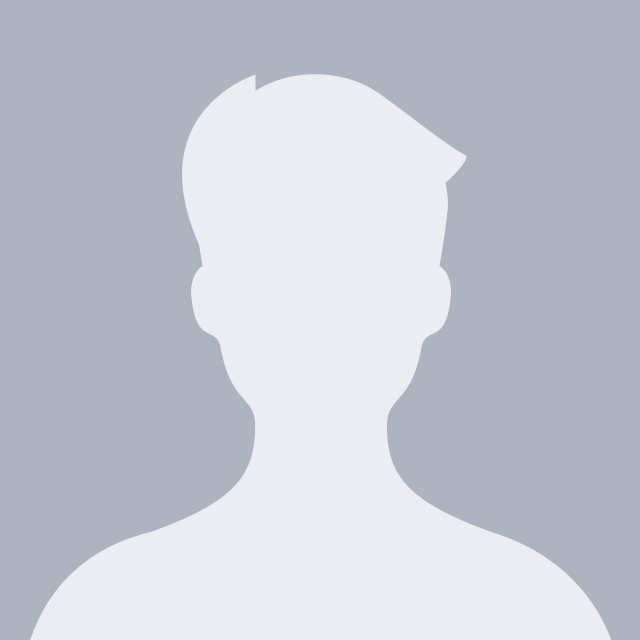
Mahasiswa Universitas Mataram
Topik :












