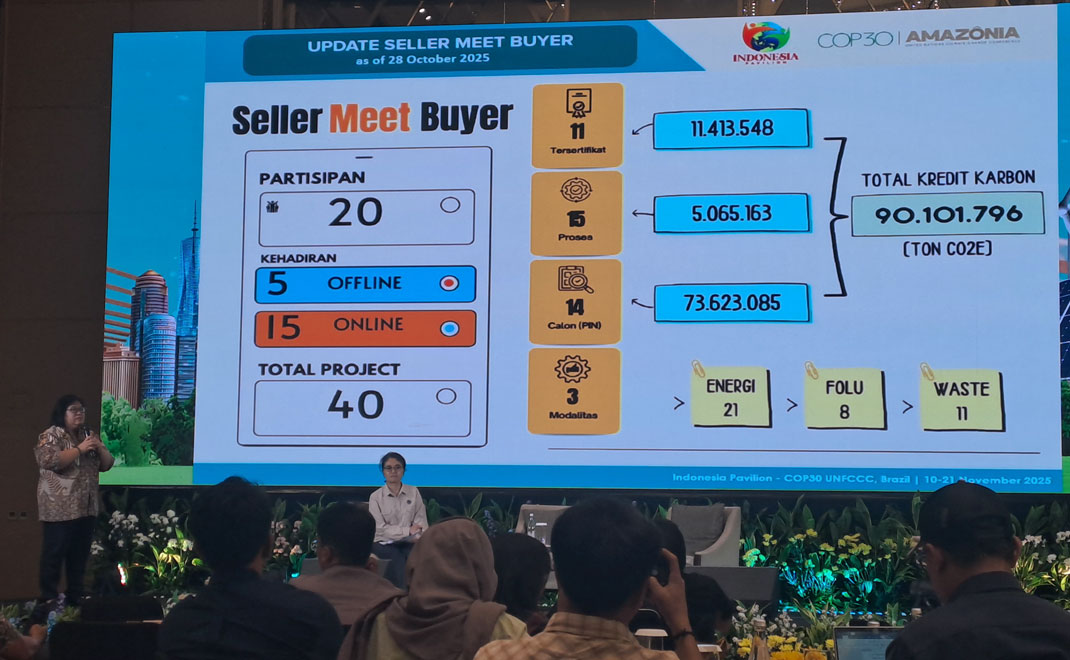KETIKA sebuah rancangan undang-undang dibahas, atau ada perubahan atas undang-undang yang sedang berjalan, kita berharap ada perubahan pula dalam komitmen dan praktiknya. Tentu ke arah yang lebih baik karena kebijakan dibuat untuk membuat kita yang diaturnya memiliki hidup lebih bermakna, membuat bumi tempat kita berpijak menjadi lebih sentosa.
Sayangnya, acap kali harapan tinggal harapan. Ketentuan dalam pasal-pasal sebuah undang-undang tidak dilaksanakan atau peraturan turunan yang membuat ketentuan dalam konstitusi beroperasi tidak pernah dibuat, hingga undang-undang itu diganti dengan yang lebih baru.
Atau tak ada ketentuan dalam undang-undang tapi pelaksanaannya masif. Perhutanan sosial dan restorasi ekosistem adalah salah dua dalam kebijakan kehutanan yang berjalan di lapangan, meski tak ada ketentuannya dalam undang-undang.
Banyak orang masih memakai logika linier bahwa undang-undang berubah praktiknya pun berubah. Demikian pula dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, banyak harapan baik, meski lebih banyak risiko buruk, kendati jarang yang menyoal praktik melaksanakannya.
Sudah bukan rahasia lagi ketentuan dalam sebuah undang-undang, karena memihak kepentingan tertentu, ketika dibuat sebisa mungkin sulit dilaksanakan pemerintah. DPR sebagai lembaga pengawas juga acap dibuat tak bergeming bahkan sejak pasalnya dibuat.
Contoh yang kini jadi klasik adalah Undang-Undang Pokok Agraria yang hingga saat ini tidak pernah ada aturan turunannya. Demikian pula dengan Undang-Undang Kehutanan, tidak pernah ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat sesuai mandat pasal 67.
Keputusan peradilan, seperti putusan Komisi Informasi Pusat maupun oleh Mahkamah Agung, juga tidak dijalankan pemerintah. Misalnya keterbukaan informasi mengenai perizinan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Meskipun hal itu keliru, fakta politik menunjukkan bahwa pelanggaran semacam itu tidak punya makna apa pun. Jadi, bisa saja ketentuan-ketentuan yang merugikan publik dalam UU Cipta Kerja tak dilaksanakan pemerintah. Sebaliknya, ketentuan yang menguntungkan meski tak ada dalam undang-undang bisa dilaksanakan dengan gencar, seperti dalam hal perhutanan sosial dan restorasi ekosistem.
Fakta-fakta itu menunjukkan, di dunia nyata, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah penyelesaian masalah, bukan ketentuan-ketentuannya. Pada beberapa hal, kemunculan sebuah undang-undang malah memicu masalah baru atau mewadahi tindakan yang tak adil.
Dalam korupsi pemanfaatan sumber daya negara (state capture corruption), keputusan politik menghasilkan peraturan, pedoman atau norma yang semuanya sah secara prosedur, tetapi isinya menguntungkan kelompok tertentu. Bedanya, jika korupsi jenis ini bisa dibuktikan pelanggarannya, pelakunya bisa dihukum. Bagaimana dengan undang-undang yang tidak adil?
Pada tahap tertentu, kita bisa mengandalkan birokrasi dalam melaksanakan atau tak melaksanakan peraturan. Saya menyebutnya “birokrasi”, bukan pemerintah atau eksekutif, karena dalam praktiknya sangat tergantung dan ditentukan oleh kepemimpinan.
Selama lima tahun saya bersama tim penilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menelaah bentuk-bentuk inovasi kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menilai green leadership.
Dari pengamatan saya, perubahan menuju perbaikan umumnya dipicu oleh inisiatif pemimpin yang mampu membentuk struktur untuk diikuti oleh birokrasi di bawahnya. Mereka umumnya mampu membalik teori perilaku birokrasi bahwa tujuan birokrasi untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri—seperti perilaku konsumen yang mengandung motif maksimalisasi kesejahteraan pribadi, atau perilaku perusahaan yang didorong maksimalisasi keuntungan.
Pengalaman para kepala daerah itu menunjukkan membalik perilaku birokrasi sangat tidak mudah, pasang-surut, dengan berbagai dampak buruk dan memerlukan waktu lama memulihkannya kembali. Dalam “Bureaucratic behavior is even more damaging than you thought” yang menukil riset Harvard Business Review, Scott Mautz mengkonfirmasi teori birokrasi di atas.
Perkembangan birokrasi hampir selalu membuat lapisan-lapisan pelayanan sehingga proses administrasi melambat. Sementara pemakaian tambahan waktu tak menghasilkan nilai tambah. Mengapa bisa terjadi? Karena birokrat juga bergumul dengan kebutuhan mereka sendiri sebagai personal sosial: menyelesaikan perselisihan, memperebutkan sumber daya, memilah masalah private, menegosiasikan target, dan tugas domestik lainnya seperti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas birokrasi.
Benarkah dengan memangkas regulasi, birokrasi bisa lebih efektif dan—dengan begitu—lapangan kerja bisa terbuka?
Selama 30 tahun bergelut dengan kebijakan dan mengamati praktik-praktiknya saya melihat peraturan banyak berubah, tapi kerja birokrasi relatif sama. Artinya, sebagus apa pun aturannya, jika mental birokrat kita tak menyentuh semangat perubahan dalam undang-undang, cita-cita yang ada di dalamnya belum tentu berubah juga.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :