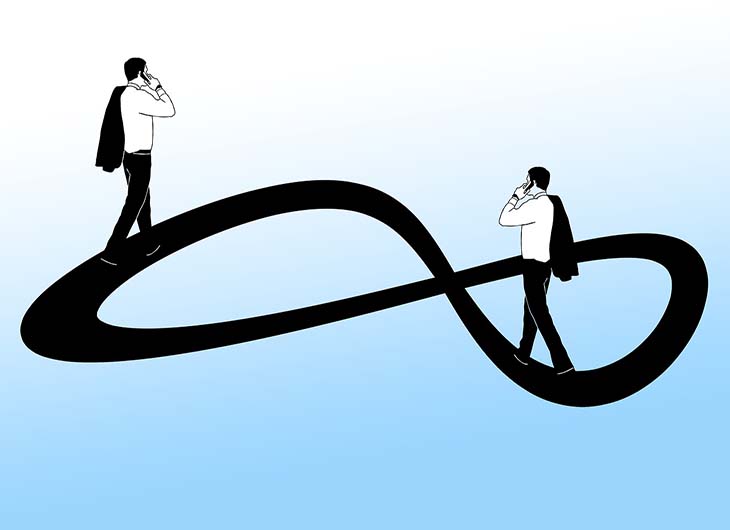
LEBARAN di masa pandemi membuat ruang silaturahmi sangat terbatas. Hanya dengan beberapa orang saja saya bisa bertemu secara langsung, sanak, saudara, dan tetangga dekat, selebihnya saling menyapa melalui pertemuan online. Akibatnya, tidak seperti dalam kondisi normal, percakapan tidak diintervensi oleh cerita-cerita keluarga dan hal-hal lain terkait Lebaran, tetapi menyoal perkembangan kebijakan publik, sosial, maupun politik, dengan teman-teman sejawat.
Saya mencatat beberapa kontradiksi dalam kebijakan publik. Misalnya, Presiden mencanangkan atau menegaskan segera dijalankan 245 proyek strategis nasional, termasuk reforma agraria, perhutanan soaial dan peremajaan sawit rakyat. Informasi itu penting, terutama karena proyek strategis biasanya hanya mencakup investasi usaha-usaha besar. Ironisnya, kriminalisasi petani serta pengusiran mereka akibat tersisih oleh proyek-proyek investasi besar, seperti tambang, kebun dan hutan, terus terjadi.
Ada penegasan kebijakan nasional yang mengarah pada “Kampus Merdeka”, yang ditegaskan dalam media komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi April 2020. Tapi kriminalisasi dan ancaman terhadap kebebasan akademik malah naik. Tekanan itu terjadi, misalnya, di Universitas Syah Kuala Aceh dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Dalam media komunikasi Kementerian Pendidikan itu juga dikabarkan adanya Rapat Koordinasi Nasional Kebudayaan 2020 dengan tema “Gotong Royong Memajukan Budaya Melalui Sinergi Pusat dan Daerah”. Padahal dalam RUU Cipta Kerja sumber norma kebudayaan bangsa sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, yang tertuang dalam perubahan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dihapus. Demikian pula hampir seluruh kewenangan daerah dalam pendidikan juga dihapus.
Saya coba menelaah paradoks fakta-fakta tersebut melalui salah satu konsep dasar dalam tinjauan ekonomi politik yaitu statisme (statism).
Mike Rappaport (2012), Guru Besar Hukum Yayasan Darling, Universitas San Diego, mengatakan bahwa statisme mirip dengan “isme” negatif lainnya, yang mengandalkan kekuasaan negara secara berlebihan dan cenderung berbahaya dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam bentuk yang lebih ekstrem, seperti halnya fasisme, terdapat pemujaan yang hampir religius atas kekuasaan negara, tanpa menyadari bahwa peran negara secara empiris bisa mendukung kebaikan atau keburukan.
Rapapport juga menyebut statisme sebagai wakil utama liberalisme kesejahteraan modern, sekaligus menjadi penyebab kebangkrutannya yang akan datang. Ia menunjukkan bagaimana statisme dari waktu ke waktu menginfeksi model standar ekonomi. Pertanyaan wajib dalam membahas soal itu adalah: apakah masalah yang dihadapi harus dilakukan melalui mekanisme pasar? Melalui kebebasan bertransaksi yang memungkinkan efisiensi meski tak menyelesaikan ketidakadilan? Atau oleh pemerintah mengintervensi pasar melalui kebijakan?
Dalam kasus itu, Rapapport mengingatkan bahwa manusia tidak sepenuhnya tertarik pada urusan publik. Kita cenderung memikirkan diri sendiri. Kita tahu ekonom neoklasik membuat asumsi bahwa pelaku pasar tertarik pada diri sendiri dan pemerintah tertarik kepada publik. “Itu jelas bias pemerintah," katanya. Ia menyitir pendapat James Buchanan (1919-2013), pemegang Nobel Ekonomi 1986, dan Gordon Tullock (1922-2014), guru besar di George Mason University School of Law. Dua ahli teori pilihan publik itu menyatakan bahwa aktor pemerintah sering bertindak mempromosikan kepentingan mereka sendiri.
Rumusan Tullock tecermin secara empiris dalam perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang sudah disahkan. Dalam beleid itu setidaknya ada 19 pasal direvisi untuk menghapus kewenangan daerah, yakni pasal 4, 7, 8, 11, 15, 21, 67, 72, 73, 93, 105, 113, 118, 119, 121, 123, 140, 141, dan 142. Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelidikan dan penelitian pertambangan dihapus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diberi hak memberikan penugasan kepada lembaga riset, perusahaan negara, perusahaan daerah, dan badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian, dalam menentukan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Hal itu berarti negara menghapus intervensinya atas perilaku swasta yang dikendalikan oleh pasar. Dengan kata lain, Menteri Energi bisa melakukan swastanisasi penyelidikan calon areal tambang, yang menentukan posisi penting untuk menentukan data sumber daya dan cadangan mineral.
Demikian pula ayat 1 Pasal 27 yang menyebut kewajiban pemerintah menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) juga dihapus. Ketentuan WPN diperlukan sebagai kebijakan konservasi alam yang tercantum dalam ayat 3 pasal yang sama juga dihapus.
UU Minerba itu juga mengatur Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada Pasal 35 ayat 3, dengan memberi solusi dan jaminan keberlanjutan perusahaan raksasa eks-pemegang Kontrak Karya (KK), seperti PT Freeport Indonesia, atau pemegang Perjanjan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Dalam ketentuan lama, KK dan PKP2B yang telah habis masa berlakunya harus kembali ke negara sebagai WPN untuk dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMD sebagai penerusnya. Kini, dalam Pasal 28 ayat 1, area konsesi tambang itu diubah menjadi WUPK, tanpa harus dikembalikan ke negara terlebih dahulu sebagai WPN dan dilelang.
Fakta-fakta paradoksal di atas menunjukkan bahwa wawasan yang selalu mengkritik pasar dan mendukung pemerintah tidak selalu dibenarkan, manakala koalisi antara kepentingan pasar dan pemerintah terjadi. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kegagalan pasar yang tidak mampu menghadirkan efisiensi dan keadilan ekonomi adalah juga kegagalan pemerintah yang menjadi bagian dari pasar itu sendiri. Itu artinya, pada titik ekstrem, agensi administratif atau birokrasi juga tidak mungkin bertindak rasional karena mengalami bias statisme yang sama.
Tobias Bach and Kai Wegrich (2019), dalam Blind Spot, Biased Attention and the Politic of Non-coordination, soal-soal ini disebut sebagai bias politik birokrasi. Disadari atau tidak, anggota dan tentu saja pimpinan birokrasi bertujuan memelihara dan melindungi kepentingan lembaganya. Itu bisa diartikan bahwa suatu lembaga negara bisa berjalan sebagai aktor politik, daripada berjalan seperti roda gigi yang berputar seiring roda-roda lain dalam pemerintahan.
Dengan begitu narasi publik (public sphere) yang dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat, media, lembaga penelitian maupun berbagai organisasi non profit menjadi sangat penting, sebagai kekuatan sosial ketiga, untuk menguraikan dan mendekonstruksi kekuasaan struktural statisme dalam pembuatan kebijakan publik.
Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :















