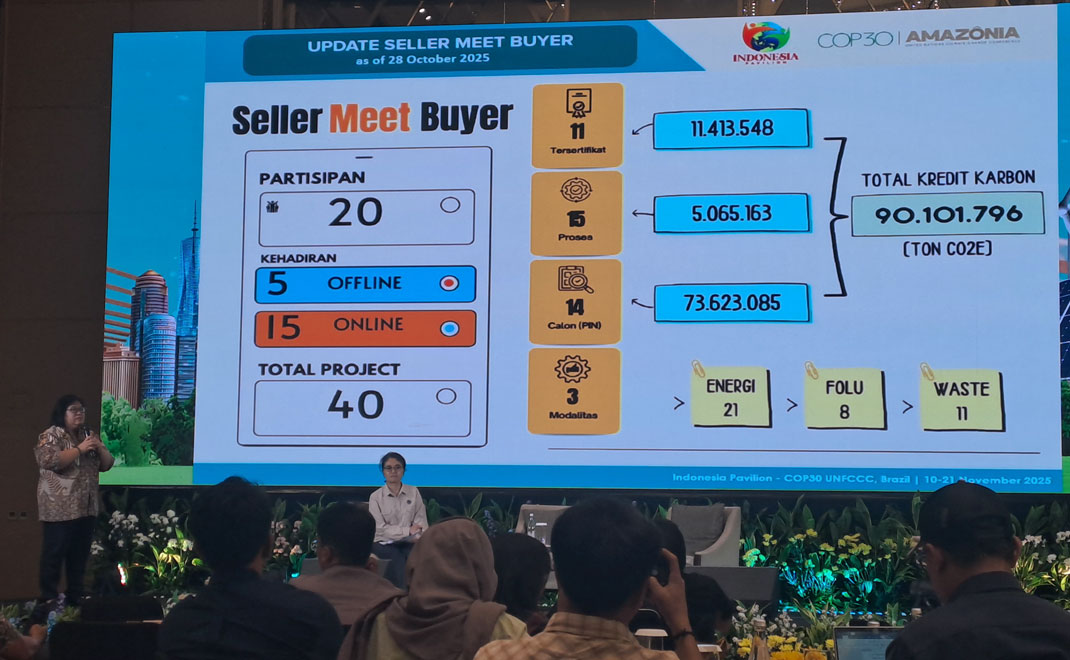PERDEBATAN tentang penyebab sebuah bencana selalu berulang tiap kali kita tertimpa bencana itu. Rekomendasi penanggulangannya selalu muncul dalam pelbagai bentuk di media konvensional maupun media sosial, tiap kali sebuah bencana timbul. Teori, informasi, hingga investigasi bencana itu pun segera pula bermunculan dalam pelbagai segi. Mengapa segala perdebatan itu tak bisa mencegah bencana hingga kerusakan dan korban saat bencana berikutnya datang?
Secara ideal, informasi, hasil investigasi, dan teori memandu kita mempelajari bencana lalu menghindarkan diri dari kerusakan lebih parah di masa mendatang. Bencana adalah keniscayaan karena bumi bergerak, hukum alam bekerja jika ada hukumnya yang berubah akibat aktivitas kita. Sesungguhnya kita tahu, tetapi mengapa kita hanya bisa menunggu? Variasi dari judul cerita pendek Leo Tolstoy yang terbit 1872 ini selalu teringat tiap kali saya tahu “kita tahu tapi tak melakukan sesuatu”.
Mungkin karena ada perbedaan antara interpretasi teori dengan kondisi nyata atau empiris tersebut. Menurut saya, kondisi nyata itu bukan apa yang terlihat dan terukur. “Kondisi nyata” itu bukan kondisi bio-fisik yang rusak berserta penyebab-penyebab fisiknya (rumah yang rusak karena banjir akibat hutan di atasnya gundul, misalnya). Kenyataan di sini adalah semua kejadian dan hal yang ada di balik rumah-rumah rusak, hutan gundul, sungai meluap.
Dalam ilmu kebijakan terdapat cara kerja untuk mencari hal-hal di balik suatu kejadian. Apabila kita masukkan ilmu politik—ilmu yang membicarakan sumber maupun cara bekerjanya kekuasaan—muncul pertanyaan: Apakah bencana yang terus berlangsung di Indonesia akibat lemahnya dukungan politik dalam pencegahan dan pengendaliannya?
Di situ bisa kita amati bahwa pengendalian bencana sebagai kepentingan publik itu sesungguhnya sangat rentan. Secara de facto, “ruang publik” senantiasa cair dan terbuka untuk dikuasai “apa pun” dan “siapa pun”, walaupun sistem politik telah memberi pedoman, peraturan maupun undang-undang, bagaimana sistem kekuasaan bekerja.
Formulasi standar prosedural itu, oleh Tania Murray Li, guru besar Antropologi Universitas Toronto, disebut sebagai teknikalisasi masalah. Isinya serangkaian pedoman, teknologi, indikator statistik, konsensus ahli untuk menetapkan pengelolaan teknokratik terhadap ekonomi dan lingkungan hidup.
Banyak penelitian yang membuktikan pendekatan standar seperti itu bukan hanya gagal menghasilkan fungsi-fungsi ekologi, tapi gagal mempertimbangkan pola perubahan demografi dan perubahan preferensi maupun perilaku masyarakat. Awal bulan ini, misalnya, saya menguji disertasi Dian Afriyanie berjudul “Perencanaan Ruang Hijau Perkotaan untuk Resiliensi Banjir Melalui Pendekatan Socio-Ecological Resilience” di Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Ia menyimpulkan persis sama seperti itu.
Dalam sistem yang lebih besar, aktor politik yang membawa kepentingan kelompoknya, telah berhasil menetapkan sebab-akibat yang membentuk narasi kebijakan pengendalian bencana. Namun mereka tak menghubungkannya dengan proses pemiskinan masyarakat maupun hilangnya hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik. Padahal itu dilindungi konstitusi.
Konsep dan pertentangan ini kita pelajari dalam pembangunan ekonomi. Di dalamnya sudah jelas kita pelajari merawat fungsi lingkungan hidup dan pencegahan bencana adalah menempatkan ilmu ekonomi menjadi bagian dari ilmu keselamatan sosial (societal safety sciences). Karena itu, paradigma ini memihak kepentingan kelompok rentan dalam arena kontestasi pemanfaatan ruang.
Ilmu keselamatan sosial ini pertama kali dibahas dan diajarkan oleh Universitas Kansai, Jepang. Mereka belajar dari kejadian-kejadian di Jepang, yang menderita akibat 99 serangan mega-bencana sejak tahun 500, dan berulang hampir setiap 15 tahun sekali. Dasar samudra selatan barat daya Jepang, palung Nankai, bergerak secara paralel dengan garis pantai menghasilkan gempa di kedalaman 4.000 meter yang terjadi tiap 100-150 tahun sejak 684.
Sejarah bencana itu terdapat dalam buku “Science of Societal Safety: Living at Times of Risks and Disasters” oleh Seiji Abe, dkk (2018). Isinya membahas pentingnya pengembangan ilmu keselamatan sosial. Sekolah Pascasarjana Ilmu-ilmu Keselamatan Sosial, Universitas Kansai, secara aktif meneliti pendidikan pencegahan dan mitigasi bencana, serta terus mengembangkan tiga bidang dasar sains dengan sistem teknik, sosial, dan humaniora.
Sistem sains dan teknik berkontribusi mencegah dan memitigasi bencana dengan memperjelas mekanismenya. Sistem sosial mencakup kebijakan administratif tentang bencana dan kerusakan, hukum yang mendasarinya, ekonomi dan operasi, maupun desain sistem sosial. Sedangkan sistem humaniora menangani psikologi dan etika orang dalam bencana dan korban, komunikasi antar manusia maupun komunikasi antar masyarakat.
Para ilmuwan di Kansai itu merancang sekolah dengan tiga bidang terserbu dengan sengaja membuatnya secara inklusif terhadap bidang ilmu lain. Fokusnya tetap pada penguatan sintesis untuk mendapatkan penyelesaian persoalan keselamatan sosial, baik secara konseptual maupun empiris. Para peneliti yang peduli dengan keselamatan sosial mengakui perlunya pendekatan interdisipliner untuk menangani masalah di lapangan.
Bagaimanapun, ilmu keselamatan sosial, bukanlah bidang akademik yang diakui secara internasional. Namun Universitas Kansai, dengan dukungan politik nasional Jepang, tetap mendirikan fakultas dengan nama ilmu itu pada 2010, dengan memakai frasa “Societal Safety Sciences” dalam bahasa Inggris.
Dari cerita Seiji Abe dkk, kita bisa melihat bagaimana keteguhan politik Jepang telah memihak kebutuhan bangsa Jepang. Politik Jepang telah melahirkan politik bencana untuk menyelamatkan bangsa Jepang. Politik bertaut erat dengan kepentingan orang banyak. Ke mana arah politik bencana Indonesia berjalan?
Gambar oleh Hermann Traub dari Pixabay
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :