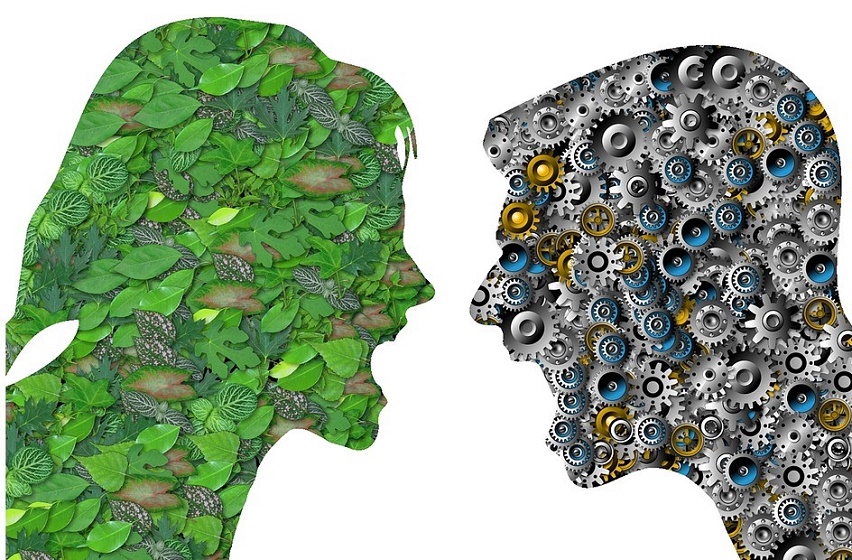
The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words.
~ Philip K. Dick
SAYA merasa kita sudah cukup paham mengenai konflik tanah. Tanpa harus merujuk definisi tanah dalam undang-undang, penyebab konflik tanah terentang dari soal ketiadaan bukti kepemilikan sebagai syarat administrasi, tingginya ketimpangan penguasaan, maupun korupsi.
Data akumulasi konflik tanah yang dicatat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Desember 2018 sebanyak 10.802 kasus. Sengketa itu paling sering terjadi antar perorangan sebanyak 6.071 (56%), konflik antara masyarakat dan pemerintah sebanyak 2.866 kasus (26%), diikuti sengketa antara perorangan dan badan hukum sebanyak 1.668 kasus (16%). Selanjutnya, konflik yang terjadi antar badan hukum sebanyak 131 kasus (1,4%). Terakhir, sengketa antar-kelompok masyarakat sejumlah 66 kasus (0,6%). Pada 2018 saja terjadi 2.546 sengketa tanah.
Dari laporan itu terlihat sudah ada upaya penyelesaian, namun umumnya masih terbatas pada persoalan administrasi. Padahal, sengketa tanah juga timbul akibat merajalelanya mafia tanah. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian ATR/BPN sudah menandatangani nota kesepahaman dengan kepolisian. Belum terlihat sejauh mana efektivitas kesepakatan ini.
Korupsi Tanah
Problem utama konflik tanah ini adalah tumpang-tindih izin. Investasi, yang bermula dari perizinan lokasi, berdasarkan informasi peta yang berbeda di lembaga pemberi izin tiap jenjang. Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) mencatat indikasi tumpang tindih izin lahan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Di pulau Sumatera tumpang tindih izin lahan sebanyak 37,63%, Kalimantan sebanyak 42,12%, Jawa 49,61%, Bali dan Nusa Tenggara 50,38%, Sulawesi 42,95%, serta Maluku dan Papua 26,93%.
Untuk mengurai dan mengetahui penyebab tumpang-tindih itu kita layak melihatnya dari perspektif korupsi.
Selama ini, korupsi tanah melibatkan pemilik kewenangan dan kekuasaan untuk memutuskan siapa yang memiliki dan mengakses lahan. Di situ kolusi hanya mungkin terjadi apabila mereka yang memiliki kekuasaan dan kontrol atas tanah menyalahgunakan otoritasnya itu. Hal itu hanya dimungkinkan jika tak ada informasi yang bisa diakses oleh orang banyak.
Sudah sejak lama kita tahu bahwa dalam korupsi tanah, penyebabnya adalah manajemen birokrasi yang buruk. Dalam What is Land Corruption? (Tranparency International, 2016), korupsi tanah disebutkan karena dipicu persoalan kedaulatan ekonomi dan pembangunan melalui pemberian investasi dan akses tanah kepada elite, dengan imbalan perdagangan mineral, misalnya. Pemberian akses dari negara kepada warga negara itu sebermula menjamurnya korupsi melalui suap, perampasan tanah, dan pencabutan hak milik warga negara lain yang lebih banyak.
Dalam keadaan seperti itu, istilah pembangunan dan kepentingan nasional telah digunakan sebagai alat merampas hak kaum miskin dengan lewat kesepakatan gelap antara aktor negara dan pemodal. Dengan begitu tanah menjadi instrumen politik.
Akibat akhirnya adalah korupsi tanah membuat problem besar tata ruang di Indonesia. Data KPK (2017), misalnya, menunjukkan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit tumpang tindih dengan izin pertambangan seluas 3,01 juta hektare, tumpang tindih dengan izin hutan tanaman industri seluas 534 ribu hektare, dan hutan alam seluas 349 ribu hektare, serta menempati kubah gambut yang dilindungi seluas 801 ribu hektare.
Bahkan di Riau, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, tata ruang provinsi 2018-2038 sengaja dirancang untuk hanya menentukan 21.248 hektare luas ekosistem gambut yang berfungsi lindung. Padahal, seharusnya gambut lindung seluas 2,3 juta hektare. Mahkamah Agung kini tengah menilai peraturan daerah tersebut karena sejumlah kalangan mengajukan keberatan.
Maka, banyaknya konflik tanah bukan akibat kelangkaan lahan atau meningkatnya populasi manusia, atau sekadar persoalan administrasi, tetapi akibat buruknya tata kelola dan korupsi tanah, melalui politik dan kebijakan.
Karena itu para akademisi dan penggerak organisasi sosial sejak 2001 membahas soal ini dan mengadvokasinya hingga parlemen. Hasilnya berupa Ketetapan MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Ketetapan itu memandatkan sinkronisasi undang-undang untuk menyelesaikan persoalan tanah dan sumber-sumber agraria. Sejak itu pula tak ada lagi dikotomi agraria dan sumber daya alam.
Setelah itu, berbagai organisasi masyarakat sipil maupun akademisi secara intensif mengawal perbaikan aturan turunannya. Kata-kata kunci seperti “transparansi”, “partisipasi”, “akuntabilitas”, “pemberdayaan”, “keadilan”, “efisiensi”, “hak asasi manusia”, “anti-korupsi”, juga kata-kata klasik seperti “koordinasi” didorong masuk dalam pelbagai aturan. Semua kata itu akhirnya masuk di berbagai teks peraturan-perundangan, namun dengan arti berbeda seperti usul maupun makna awalnya.
Dalam praktiknya, pengertian kata-kata itu menyimpang bahkan maknanya dipersempit sesuai kebutuhan administrasi. Misalnya, kebutuhan “social mapping” diganti dengan “peta”, “koordinasi” diganti dengan “rapat”, konflik dan sengketa tanah hanya dianggap sebagai persoalan administrasi. Kepentingan politik telah melencengkan makna kata-kata itu.
Kata "koordinasi" mestinya menjadi penting, karena tidak ada satu pun lembaga bisa mengerjakan semua hal yang dibutuhkan masyarakat—apalagi menyangkut penyelesaian sengketa tanah akibat korupsi tanah—sendirian. Sebagaimana para pemain sepak bola dalam sebuah tim mesti berkoordinasi dengan saling umpan bola untuk membuat gol. Dalam hal pemerintah kita, mereka seperti punya gol sendiri-sendiri. Koordinasi hanya dimaknai sebagai rapat yang ditunjukkan hanya dengan absensi kehadiran.
Kata-kata Philip Dick terngiang kembali. Agaknya, menyelesaikan konflik tanah bahkan harus dimulai dengan mengembalikan kata dalam pelbagai aturan ke dalam pengertian yang seharusnya, sebelum jadi paradigma, lalu jadi tindakan nyata.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :















