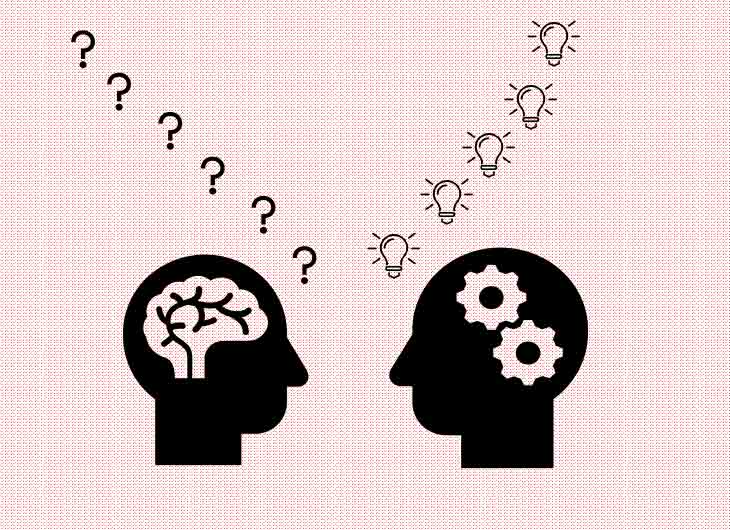
BIASANYA kita akan senang jika mengetahui atau mendengar ada seseorang atau lembaga yang membuat inovasi untuk menyelesaikan problem-problem dalam kehidupan nyata. Bahkan kita mungkin bangga karena peradaban terus maju, masalah-masalah telah mendapat solusi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan.
Sebaliknya, kita akan senewen jika kita tahu bahwa inovasi tidak tumbuh karena terhambat oleh hal-hal teknis. Dalam rehabilitasi hutan dan lahan, misalnya, kita membuat solusinya dengan mengurai satu-per-satu: dari mengolah tanah, memperoleh bibit, menyemai, menanam, memupuk, memelihara. Bahkan mungkin ada pelatihan untuk mendukung tiap-tiap tahap itu, dengan harapan muncul inovasi dari sana.
Sebuah harapan yang agaknya sia-sia. Pengalaman saya bergelut lebih dari 20 tahun dalam urusan kebijakan, inovasi tak muncul karena kita terjebak pada hal-hal teknis yang rigid itu. Sebab, yang harus kita lakukan sebenarnya mengubah perilaku (kebijakan) untuk menciptakan inovasi, bukan melulu berkuta dalam cara mengerjakannya (prosedur).
Kita tahu berpikir kritis adalah fase penting dalam menemukan inovasi. Bagaimana bila berpikir kritis itu tidak sesuai prosedur? Bagaimana bila permasalahan nyata di lapangan itu, secara administratif, bukan ukuran kinerja? Tentu saja, jika kita persempit membicarakan inovasi dalam birokrasi kita.
Pertanyaan semacam itu, yang menentukan cara berpikir seperti itu, menyebabkan birokrasi kita mengidap bias perhatian atau titik buta (blind spot) terhadap masalah riil di lapangan. Buku yang disunting Tobias Bach dan Kai Wegrich (2019) “Blind Spots, Biased Attention, and the Politics of Non-Coordination” menyebut bias perhatian itu menjadi sumber kegagalan atau menghambat inovasi kebijakan.
Tentu ada beberapa pengecualian. Selalu saja ada setitik harapan dalam lorong yang gelap. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Way Seputih Way Sekampung di Lampung sudah menjalankan berbagai eksperimen dan teknologi inovatif tepat guna di banyak wilayah.
Inovasi itu, misalnya, teknologi reklamasi lahan bekas tambang timah, teknik budidaya dan pengolahan produk dari gaharu, inokulasi pohon gaharu dengan bio-serum, model pengelolaan air permukaan berbasis eduwisata. Bahkan membudidayakan buah-buahan lokal yang mampu bersaing dengan buah impor ataupun usaha ternak burung oleh kelompok petani.
Sekali waktu ia mengatakan kepada saya bahwa kawasan hutan selalu dianggap sebagai domain hukum, bukan domain sosial. Akibatnya, perangkat kerja mengelola hutan tidak disiapkan untuk memahami permasalahan sosial, termasuk konflik sosial. Dalam pembuatan bibit pohon, misalnya, yang terpenting bukan fisik bibitnya, tapi jiwa sosial dalam prosesnya.
Sebab di sana ada komunikasi, ada tanya-jawab, ada permintaan, ada kecurigaan, ada ketidakpercayaan maupun saling menyembunyikan identitas. Semua hal itu sesungguhnya memerlukan empati, pengalaman, keteguhan, kesadaran, antisipasi-antisipasi, sehingga lahir sebuah landasan kerja, yang biasa disebut modal sosial. Bandingkan, misalnya, jika bibit itu disediakan kontraktor yang ditunjuk secara administrasi. Proses interaksi itu akan hilang. Ujungnya, hutan terbengkalai.
Karena itu pendekatan birokrasi secara sosial akan berfungsi menguatkan komitmen masyarakat. Mereka akan terdorong menjadi penggerak masyarakat, melakukan inovasi, hingga tumbuhnya jiwa kewirausahaan.
Menjadi petani itu risikonya besar. Karena itu, birokrasi mesti membuat pendekatan kepada masyarakat tak semata atau terbatas pada pembuatan surat, yang menjadi tugas dan fungsinya.
Maka, peta lokasi suatu program lingkungan tak hanya dipandang sebagai peta spasial belaka. Seorang birokrat perlu juga memahami peta aktor, jaringan, dan struktur masyarakat yang akan terlibat di dalamnya.
Jika cara pandangnya seperti ini, maka kawasan hutan tak akan dipersepsikan sebatas hukum, yang berhenti di penunjukan dan penetapan. Sebab hutan adalah sebuah ruang hidup sosial-ekonomi masyarakat. Inilah cara berpikir kritis yang seharusnya dimiliki oleh para birokrat kita.
Ironisnya, dalam birokrasi landasan kerja inovatif seperti itu punya porsi sangat kecil. Bahkan terlihat dari cara kita memperlakukannya. “Pengadaan bibit” itu akan masuk kategori “pengadaan barang”, sebuah kategori tanpa jiwa, tanpa berhubungan dengan subyek-subyek. Bibit dianggap sekadar mur, yang dapat dilekatkan pada baut, yang tak memerlukan keteguhan, empati, kesadaran, maupun kepercayaan.
Dengan keadaan seperti itu, para birokrat yang inovatif acap bersiasat terhadap “kebenaran”, yaitu ketentuan administrasi dan peraturan yang harus mereka patuhi. Di birokrasi pemerintahan, regulasi program, kegiatan, keuangan beserta standar-standarnya, harus sesuai aturan agar tak celaka ketika dijalankan.
Dengan risiko di kemudian hari yang membuat jeri itu, para inovator kehutanan acap mencari sendiri pendanaan untuk menopang inovasi mereka. Meski pun cara ini riskan juga karena tak sesuai aturan, kendati tujuannya menyelamatkan birokrasi agar gagasan mereka tak mentok di tahapan teknis.
Akumulasi persoalan inovasi di atas, apabila tidak segera dipecahkan, bisa menurunkan kredibilitas kebijakan dan birokrasi di lapangan. Dalam publikasi klasik “The Effect of Policy-Maker Reputation and Credibility on Public Expectations” (1996), Granato mengatakan bahwa reputasi kebijakan sangat menentukan harapan publik.
Mungkin itulah alasan di balik marah-marah Presiden Joko Widodo karena jengkel kementerian lambat sekali menjalankan program mereka sendiri. Jim Granato menyebut bahwa kebijakan yang tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat akan mendorong publik bersikap skeptis yang ujungnya akan menjadi ancaman bagi kebijakan itu sendiri.
Masyarakat tidak akan memperbaiki perilaku karena tidak percaya dengan tujuan sebuah kebijakan yang berdampak pada hidup mereka sehari-hari. Maka, inovasi dalam administrasi dan birokrasi menjadi kebutuhan pokok agar institusi berjalan cerdas, ringan, dan tepat. Dan, yang terpenting, menghilangkan hambatan institusional yang membuat individu di dalamnya mentok tak bisa berbuat melebihi tugas pokok dan fungsinya.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.
Topik :
















