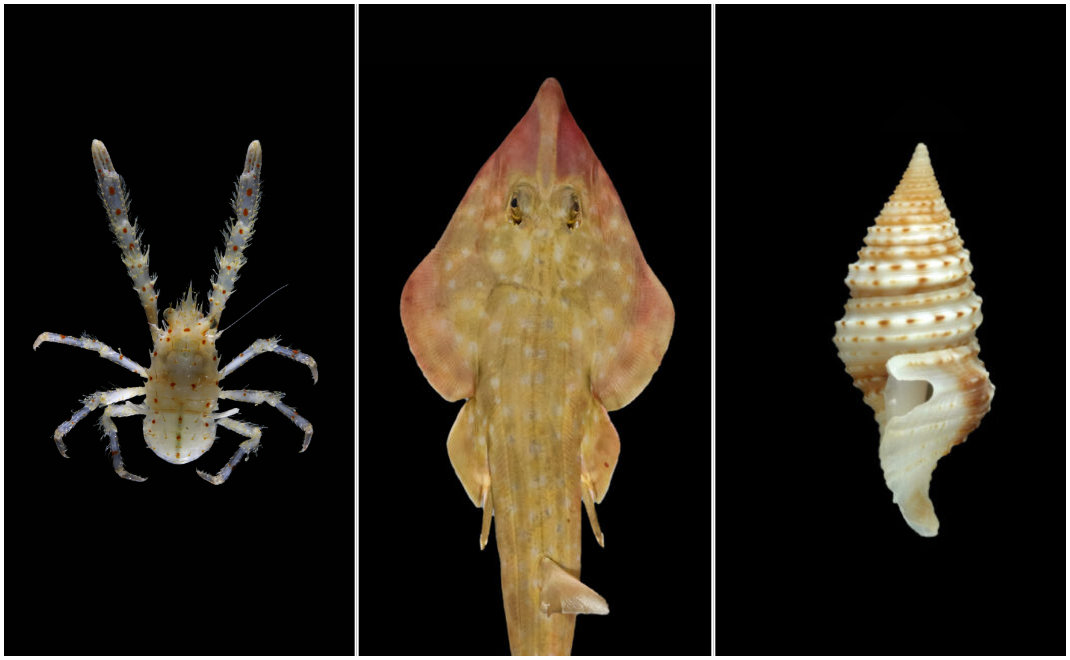TAK kenal maka tak sayang. Peribahasa ini pas menggambarkan masyarakat adat di Indonesia. Sering disebut dalam obrolan, ditulis dalam laporan, dipidatokan pejabat dan politisi, juga diadvokasi oleh para aktivis, namun masih banyak mitos, stigma, dan prasangka yang melingkupi masyarakat adat.
Sekian lama ada penyangkalan terhadap bagian dari kemajemukan Indonesia ini. Masih banyak komunitas masyarakat adat yang mengalami diskriminasi dan menerima stigma negatif. Stigma itu, antara lain, bahwa masyarakat adat adalah orang gunung, orang laut, orang hutan, atau orang dusun—predikat keren yang berkonotasi merendahkan. Mereka dianggap kotor, kumal, kucel, malas, bodoh, lugu, bau, berpenyakit, sampah masyarakat, tak terpelajar, terbelakang, kampungan, kasar, primitif, penganut ilmu hitam, percaya klenik, yang menyebabkan mereka tidak diterima secara wajar dalam pergaulan sosial. Mereka hidup mengelompok, tersekat oleh batas geografis yang mengisolasi, maupun terhalang garis imajiner akibat sekat-sekat sosial yang membuat mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain.
Koalisi masyarakat madani, yang telah sepuluh tahun ini mendorong Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, menengarai setidaknya ada enam hak masyarakat adat yang terus-menerus dilanggar. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dan melekat satu sama lain, serta harus diakui untuk pencapaian kemanusiaan hakiki bagi masyarakat adat. Hak-hak itu termasuk—namun tak terbatas pada—hak atas budaya spiritual, hak perempuan adat, hak anak dan pemuda adat, hak atas lingkungan hidup, hak atas persetujuan bebas tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent, disingkat FPIC), dan hak atas ulayat adat.
Khusus terkait wilayah adat, hak ini merupakan ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan entitas masyarakat adat, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya diatur menurut hukum adat. Badan Registrasi Wilayah Adat sejauh ini telah mengidentifikasi wilayah adat di Indonesia seluas 9,3 juta hektare. Salah satu basis legal formalnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyebutkan bahwa “Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”
Deliniasi geografis terlihat secara kasat mata di peta, menyekat dan mengisolasi masyarakat adat yang banyak tersebar di lokasi terpencil. Dalam kondisi ekstrim, batas ini menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terabaikan hak-haknya sebagai warga negara. Di sisi lain, batas imajiner bersifat tersirat, tapi bisa lebih menindas. Ia bisa berupa penolakan yang brutal, ancaman, pengusiran, pengucilan, atau pun label negatif yang disematkan pada mereka.
Sekalipun hak-hak masyarakat adat telah diakui dalam peraturan-perundangan, permasalahan masih kerap muncul terutama konflik terkait wilayah adat. Muhammad Arman, dalam Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat, mengatakan bahwa situasi masyarakat adat dewasa ini tidak jauh lebih baik. Kecenderungan politik hukum peraturan-perundangan yang mengatur keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya telah menyimpang dari semangat pembentukan NKRI, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Ahli hukum Satjipto Rahardjo menyebutkan sejumlah persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial, yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan, yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan.
Senada dengan itu, ahli hukum lainnya, Soetandyo Wignyosoebroto, persyaratan penentuan masyarakat adat secara ipso facto maupun ipso jure akan mudah ditafsirkan sebagai “pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat”.
Padahal, menurut pandangan Guru Besar Hukum Agraria Maria Sumardjono, makna “pengakuan” oleh negara dalam arti “declaratoir” (menyatakan sesuatu yang sudah ada), tidak bermakna “konstitutif” atau pemberian hak baru. Untuk menghormati hak yang sudah ada, maka pendaftaran hak tersebut melalui penegasan atau pengakuan, yang berfungsi untuk menuntaskan proses administrasi saja. Belum/tidak didaftartarkannya hak atas tanah itu tidak menafikan haknya. Bahkan dalam perkembangannya, melalui pendaftaran tanah sistematis pemerintah dapat mengambil inisiatif pendaftaran tanah hak masyarakat adat.
Carut marut ini tidak terlepas dari sejarah masyarakat adat dan lokal terpencil yang mengalami isolasi dan diskriminasi secara berlapis. Lapisan pertama adalah pengucilan oleh kebijakan negara yang selama ini mengabaikan keberadaan mereka. Lapisan kedua belum adanya penerimaan sosial dari komunitas lain yang secara pengetahuan dianggap lebih modern. Dan lapisan ketiga adalah diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang ada di masyarakat adat dan lokal terpencil di dalam internal komunitas maupun dengan eksternal komunitasnya. Lapisan ketiga ini terjadi karena pengetahuan masyarakat adat dan lokal terpencil sering kali menempatkan perempuan hanya sebatas pengelola sumber daya alam, yang tidak memiliki kewenangan dan dianggap tidak mampu membuat keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya.
Jika dilihat dari sejarah masyarakat adat dan lokal, ada dua kencenderungan masyarakat adat dan lokal terpencil yang mengemuka, yaitu: komunitas adat dan lokal terpencil yang mengeksklusi komunitasnya terhadap perubahan dari luar (sebagaimana digambarkan oleh Suku Adat Baduy di Lebak, Banten), dan komunitas lokal terpencil/terkucil yang berupaya untuk mengasimiliasi diri dengan komunitas di luar mereka (direpresentasikan oleh komunitas Cina Benteng, juga berlokasi di Banten). Keduanya mengalami kondisi yang hampir sama, yaitu eksklusi sosial, tidak adanya penerimaan komunitas lain yang lebih dominan untuk mengakui keberadaan dan hak-hak mereka secara penuh.
Komunitas yang mengekslusi dirinya kian terjepit oleh gempuran budaya tanding dari luar, derasnya arus informasi, cepatnya perubahan teknologi yang terjadi, dan pesatnya perkembangan dunia pada umumnya. Sementara masyarakat adat dan lokal terpencil ketika berproses untuk berasimiliasi dengan dunia luar juga mengalami gagap dan gegar budaya serta krisis kepercayaan diri karena mereka dianggap berbeda. Perbedaan itu kadang terlihat eksplisit dan kontras, terlebih ketika identitas fisik dan bahasa/dialek yang digunakan oleh masyarakat adat dan lokal terpencil memang berbeda dari komunitas luar. Namun tidak jarang perbedaan itu samar dan tersirat, karena cara pikir, cara hidup, norma budaya, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang mereka anut tidak sepenuhnya kasat mata.
Padahal, “tidak meninggalkan satu orang pun" (leave no one behind) merupakan prinsip utama Tujuan Pembangunan Milenium (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan; dan keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.
Ciri-ciri tersebut bisa dilihat pada beberapa kelompok dampingan Program Peduli Pilar Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang Tergantung pada Sumber Daya Alam.
Batas geografis menciptakan isolasi fisik, sedangkan batas imajiner menciptakan isolasi sosial. Keduanya menyuburkan kesenjangan dan kezaliman. Untuk melintas batas dan menempuh jarak yang jauh ini butuh nyali dan stamina yang kuat, secara fisik dan psikis. Juga butuh waktu tempuh, kesabaran ekstra, tenaga dan dana yang tidak sedikit.
Bersama-sama dengan 10 mitra CSO di daerah, Program Peduli berupaya mendekatkan jarak, meleburkan batas, meruntuhkan sekat, serta mengembangkan sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia. Itulah inti konsep inklusi sosial di Program Peduli.
Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu/kelompok sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Inkusi sosial mencakup proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu dan komunitas, sehingga mereka yang terpinggirkan dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya demi memenuhi kebutuhan dasarnya, menurut standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Melalui inklusi sosial, Program Peduli mendorong seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan setara dan bermartabat, serta memperoleh kesempatan sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun, tanpa kecuali.
Pada mulanya ada 14 mitra CSO lokal di 13 provinsi, 22 kabupaten/kota, 69 desa di Indonesia yang berkolaborasi dengan Kemitraan sebagai organisasi payung Program Peduli pada fase yang dimulai akhir tahun 2014 silam. Dalam perjalanannya, empat lembaga (yang karena berbagai alasan dan atas kesepakatan bersama) kemudian berpisah jalan untuk menempuh rute dan tujuan lain. Mereka tetap menjadi bagian dari sejarah perjalanan Program Peduli dan berhasil menorehkan catatan unik masing-masing.
Karena itu, kisah dalam buku fokus pada 10 organisasi yang mendampingi 10 masyarakat adat atau lokal. Saya menggali dan mengulik kembali nilai-nilai tradisional yang menjadi sumber pengetahuan otentik, kekayaan intelektual, dan kearifan lokal yang juga menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Penelusuran melalui para informan, membaca laporan, riset dalam jaringan, selain turun ke lapangan (karena pandemi, hanya area yang berada di dekat Jakarta). Buku ini adalah upaya merekam lika liku perjuangan masyarakat adat untuk mencapai keadaan setara bermartabat dalam bingkai kebhinekaan.
Buku ini mengajak Anda berkelana, mulai dari pedalaman Mentawai, Sumatera Barat hingga ketinggian negeri di balik awan Pipikoro, Sulawesi Tengah. Dari perkampungan kecil rombong Suku Anak Dalam di hutan yang tersisa akibat terkepung perkebunan sawit di Jambi, hingga kemeriahan lampu lampion dan tembang dayung sampan diiringi tehyan di perkampungan Cina Benteng, Tangerang. Sistematika penulisannya berdasarkan letak geografi area kerja Program Peduli, dari barat ke timur.
Di Bab 1, kita akan berkenalan dengan Masyarakat Adat Mentawai. Isolasi karena letak geografis di Dusun Bekkeiluk, Salappa’, dan Magosi di Kecamatan Siberut Selatan; Dusun Tinambu di Kecamatan Siberut Tengah; dan Kampung Gorottai di Kecamatan Siberut Utara telah menghalangi proses interaksi dan relasi yang baik dengan kelompok sosial lain dan pemerintah. Interaksi yang berlangsung sesaat, terkait dengan kepentingan yang bersifat sesaat, hanya akan membuahkan pola relasi yang transaksional dan superfisial. Interaksi dan relasi ini berdampak pada minimnya pemenuhan layanan dasar dan pembangunan di pedalaman kepulauan Mentawai. Keterbelakangan kemudian memunculkan stigma dan eksklusi dari kelompok sosial lain yang menggerus kepercayaan diri masyarakat adat untuk berdiri setara dan bermartabat dengan berbagai pihak. YCMM membantu kelompok marjinal ini keluar dari persoalan-persoalan pengucilan yang mereka hadapi. Intervensi melalui program-program pemberdayaan dan pertautan dengan kelompok sosial lain, termasuk pemerintah, ditujukan untuk memutus rantai eksklusi tersebut. Masyarakat adat di Bekkeiluk, Salappa’, Magosi dan Gorottai kini tak asing dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, baik di tingkat dusun, desa, kecamatan, hingga kabupaten. Mereka berdaya mengelola sumber dayanya sendiri.
Kita juga berjumpa dengan para penjaga rimba yang terasing, yaitu warga Suku Anak Dalam (SAD) yang diyakini sebagai suku asli Melayu Jambi di Bab 2. Suku ini semula hidup dalam kelompok-kelompok kecil (rombong) secara nomaden, mengandalkan hidup dari hasil berburu dan meramu obat. Sebagian besar rombong SAD masih hidup berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain di sepanjang lintas tengah Sumatera, yang menyulitkan mereka untuk didata dan mendapat pengakuan legal sebagai warga negara. Seiring jumlah tutupan hutan yang jauh menyusut, berbagai rombong SAD ini terlempar ke pinggir dan hanya bisa menyaksikan gerak maju proses pembangunan. Mereka hidup tanpa kepastian tanah tempat tinggal sehingga terpaksa hidup menumpang di dalam kebun sawit milik perusahaan atau milik penduduk desa nyaris tanpa sumber mata pencaharian. Bersama dengan Pundi Sumatera, Masyarakat Adat Suku Anak Dalam di Sumatera Barat dan Jambi berjuang mengikis stigma dan mendapat rekognisi sebagai masyarakat minoritas yang perlu perlindungan dan pemberdayaan. Perlahan mereka menetap, berinteraksi dan berpartisipasi dengan komunitas lain, juga mendapat layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Di Bab 3 kita bersua dengan Masyarakat Adat Suku Sawang Gantong di Bangka Belitung. Ritual adat berkah di darat, selamat di laut, dilakukan untuk merawat eksistensi dan mengangkat taraf kehidupan masyarakat adat yang nyaris punah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Penelitian Air Mata Air (LPMP Amair) bergiat mendorong inklusi sosial menuju peningkatan akses layanan dasar, penerimaan sosial dan kebijakan yang berpihak pada suku minoritas. Pendekatan pendidikan, seni budaya dan olah raga dipilih untuk menjangkau warga, termasuk pendekatan sinergi bersama dengan Pemerintah Desa Selinsing. Dalam satu tahun terakhir, tokoh masyarakat Suku Sawang Gantong kerap diundang dalam forum rapat dan pengurus Sanggar Seni Ketimang Burong sering dilibatkan pada acara seremonial di tingkat kecamatan dan kabupaten. Intensitas interaksi masyarakat sekitar dengan Suku Sawang juga meningkat, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun yang terkait hubungan jual beli hasil kerajinan, pengolahan makanan, dan kegiatan olah raga. Klub sepak bola Suku Sawang Gantong kini biasa tanding tandang atau kandang di berbagai ajang pertandingan persahabatan.
Bergeser ke pulau Jawa. Di Bab 4, kita bertemu Masyarakat Adat Baduy dan Kasepuhan di Kabupaten Lebak-Banten yang bergumul dalam dinamika sosial untuk mencapai kondisi berdaulat dan bermartabat. Mereka memiliki aspirasi untuk bebas mewujudkan eksistensi dan mengekspresikan diri dengan segala perbedaan dan keunikan mereka. Sumber penghidupan masyarakat adat Kasepuhan dan Baduy sangat bergantung pada pengelolaan Sumber Daya Alam,khususnya hutan. Mereka memegang teguh keyakinan dan menaati aturan yang telah diwariskan oleh karuhun (para leluhur/nenek moyang).
Persoalan masyarakat adat Kasepuhan antara lain konflik tenurial, stigma negatif dari kelompok tertentu yang menganggap ritual Kasepuhan sebagai ajaran sesat, dan keterbatasan dalam akses kesehatan, juga peningkatan ekonomi. Sedangkan masyarakat Baduy belum mendapatkan pengakuan negara atas kepercayaan Sunda Wiwitan, terbatasnya lahan ladang pertanian bagi Baduy Dalam, dan minimnya pemasaran produk masyarakat Baduy. Masyarakat adat lalu berhimpun dalam SABAKI (Satuan Masyarakat Adat Banten Kidul) bersama dengan Rimbawan Muda Indonesia dan jaringan masyarakat sipil lainnya mendorong Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan Peraturan Daerah Masyarakat Adat. Aturan ini krusial karena pengakuan masyarakat adat melalui Perda diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lahan dan sumber daya alam. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 merupakan dasar untuk pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan atas kedaulatan masyarakat adat dalam mengelola hutannya yang secara tegas memandatkan pengelolaan hutan adat dapat dilakukan oleh masyarakat adat serta keberadaannya tidak lagi dalam kawasan hutan negara.
Masih di pulau Jawa. Masuk Bab 5, kita menyapa para perempuan hebat “Nu Lingxiu”, Agen Perubahan Inklusi Sosial Cina Benteng dari Sungai Cisadane di Kota Tangerang, Banten. Cina Benteng merupakan satu-satunya masyarakat adat dampingan Program Peduli, bersama PPSW Jakarta, yang berlatar perkotaan. Komunitas Cina Benteng sesuai dengan definisi Masyarakat Adat Indonesia menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur dan menetap secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas, serta masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang RT RW Kota Tangerang, menyebabkan adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan perumahan. Hal itu berakibat pada perubahan mata pencaharian komunitas Cina Benteng. Lahan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk bercocok tanam. Namun, mereka tetap menjadikan Sungai Cisadane sebagai sumber utama mata pencaharian, bahkan sebagian warga yang tingkat ekonomi dan pengetahuan sanitasi relatif rendah hingga kini masih memanfaatkan sungai untuk mandi, cuci dan kakus.
Pada musim kemarau, masyarakat tergantung sepenuhnya kepada air sungai untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga karena sumur atau pompa air mengering. Kemiskinan dan anggapan bahwa warga Cina Benteng kurang terdidik membuat mereka rentan terhadap praktik-praktik diskriminasi dan eksklusi.
Kelompok perempuan menjadi bagian penting dari warga komunitas Cina Benteng yang mendorong terjadinya penerimaan sosial baik melalui pergaulannya dengan warga kebanyakan, sebagai buruh rumah tangga atau melalui kegiatan sosial dan perkawinan silang. Namun budaya asli Cina yang menempatkan perempuan lebih rendah menyulitkan perempuan mengambil peran sebagai aktor perubahan yang dapat mendorong terjadinya penerimaan sosial yang dapat melindungi warga Cina Benteng dari perlakuan diskriminatif dan eksklusi sosial. Lain dulu lain sekarang.
Perjuangan PPSW mencetak dan mendampingi kader-kader perempuan Cina Benteng berbuah manis. Berkat ibu-ibu yang percaya diri dan luwes dalam berinteraksi dan berpartisipasi di berbagai forum formal dan informal, kini warga dapat mengakses berbagai layanan kesehatan dan pendidikan, dapat mencatatkan pernikahan mereka, dan di masa pandemi Covid-19 mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai bantuan sosial, yang sebelumnya sulit diakses karena tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti KTP, KK dan lainnya.
Bergerak ke Kalimantan. Di Bab 6 kita menyaksikan masyarakat adat Dayak berusaha terus berdaya di hulu dengan tetap dalam bingkai inklusi. Didampingi oleh Yayasan Desantara, Program Peduli difokuskan untuk menjamin kepastian ruang hidup dan penghidupan Komunitas Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Lung Anai melalui tata kelola pemerintahan desa yang inklusif. Eksklusi sosial yang dirasakan oleh masyarakat Suku Dayak ini terkait erat dengan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan usaha. Sebagian anak-anak usia sekolah tidak bisa bersekolah karena harus mengikuti orang tua bekerja di ladang/kebun. Tidak ada kepastian sumber penghidupan karena tidak ada jaminan kepastian lahan. Minim penerimaan sosial. Dianggap sebagai pendatang oleh masyarakat desa sekitar. Terjadi konflik lahan antardesa akibat masuknya perusahaan-perusahaan besar. Melalui dinamika yang tak mudah, semua tantangan ini perlahan dapat diatasi dan inklusi sosial kini menjadi norma yang berlaku di sana. Selain itu, Yayasan Desantara, didukung oleh Yayasan Naladwipa, berkolaborasi dengan Program Peduli bersama Pemerintah Desa Pajanangger, membangun basis data yang kuat dalam perencanaan pembangunan pada tingkat desa. Akhir bab ini mengetengahkan cerita perubahan di Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
Berikutnya, kita ke Sulawesi. Di Bab 7 ada syair kekeluargaan pengusir keterasingan Masyarakat Adat Topo Uma di Pipikoro, Sigi. Dalam relasi dengan kekuasaan, keterbatasan isolasi fisik Topo Uma membuat mereka diremehkan dan terpinggir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari alokasi penganggaran pembangunan yang lebih kecil dibandingan dengan wilayah lain yang justru sudah lebih maju dan tak terlalu perlu dibantu. Hal ini juga dapat dilihat dari hampir tidak adanya program pemerintah baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, serta UMKM yang dilaksanakan di Pipikoro. Bersama Karsa, Topo Uma melawan stigma, diskriminasi dan eksklusi. Kini, hampir seluruh masyarakat Topo Uma telah memiliki KTP dan dokumen kependudukan sipil lainnya. Layanan kesehatan meningkat—penempatan bidan per desa yang turut mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Kesempatan pendidikan dan jumlah anak bersekolah meningkat. Pelatihan melalui sekolah lapang untuk petani kakao membuat kemampuan pertanian menjadi lebih canggih, termasuk kesempatan berusaha dengan keterampilan UMKM berikut pemasarannya. Jaringan komunikasi telah menjangkau wilayah pelosok, membawa kemajuan untuk masyarakat.
Selanjutnya, di Bab 8 kita meresapi perjuangan merebut kemerdekaan dari belenggu isolasi ala Masyarakat Adat To Balo, To Garibo, To Bentong di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Barru dan Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba. Di dua lokasi ini, Sulawesi Community Foundation mendorong program “Sipakatau-Sipakalebbi” yang dalam bahasa Bugis memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Sipakatuo-Sipakalebbi diindentikan dengan sifat yang tidak saling membeda-bedakan dan memandang manusia sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan Program Peduli yaitu mewujudkan Desa Inklusi Sosial bagi masyarakat adat dan masyarakat terisolir demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara partisipatif; peningkatan kualitas bantuan sosial dan layanan publik untuk masyarakat sekitar hutan; pengarusutamaan kebijakan inklusi dalam kegiatan ekonomi melalui ekowisata; juga implementasi pengarustamaan jender dan perlindungan anak dalam perencanaan pengelolaan desa.
Dari Sulawesi kita berangkat ke Nusa Tenggara. Bab 9 diisi cerita perubahan kelompok perempuan strata ekonomi dan kasta sosial bawah di Desa Mauramba & Meorumba di Sumba Timur, juga masyarakat adat Gumantar di Lombok Utara. Program Peduli di NTB dan NTT, dengan pendampingan oleh Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara/Samanta, diarahkan untuk meningkatkan perbaikan kebijakan lokal yang mendukung hak akses layanan dasar dan bantuan serta jaminan sosial bagi kelompok tereksklusi, termasuk kelompok perempuan yang posisinya rentan dalam masyarakat adat yang masih ketat menerapkan tradisi dalam interaksi keseharian mereka.
Terakhir, tapi bukan tujuan perjalanan paling akhir, di Bab 10 kita mengenal lebih dekat Suku Boti & Suku Bajo yang menjadi bukti keanekaragaman dan kesetaraan budaya di timur Indonesia. Bersama Yayasan Tanpa Batas, gagasan mengenai rekognisi, interaksi dan partisipasi masyarakat adat secara penuh ingin direalisasikan. Masyarakat Boti dan Bajo ingin diakui sebagai bagian sah dari Indonesia dan mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya di luar sana
Menuliskan 10 kisah ini membuat saya kian percaya, bahwa Indonesia bisa bertahan dan berdiri kokoh karena kita mengamalkan semboyan Garuda Pancasila, yakni bhinneka tunggal ika.
Untuk mengunduh buku ini silakan klik tautan ini.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Praktisi komunikasi lepas. Bukunya yang terbit pada 2021: "Inklusi Sosial: Sepuluh Kisah Peduli Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil Nusantara"
Topik :